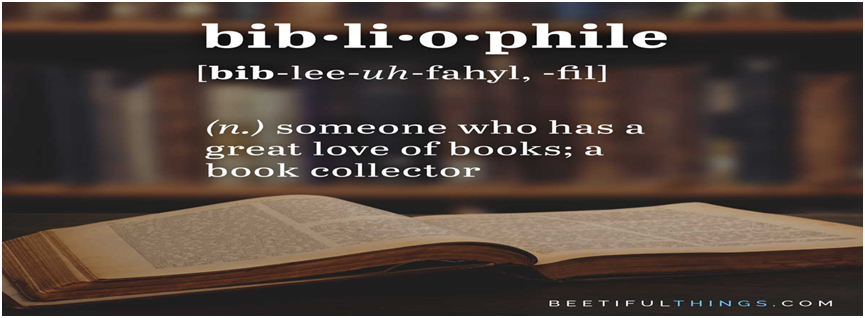***
Bangsa kita tengah berada di ambang senjakala buku. Saat negara-negara tetangga sudah mulai membiasakan diri untuk membaca, kita masih menganggap membaca sebagai sesuatu yang asing dan mewah. Ironisnya, di sana sini masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat yang berpikir pragmatis dan instan: segalanya diukur dengan uang. Akibatnya, gelar kesarjanaan menjadi prioritas utama. Membaca kemudian tidak harus untuk meningkan makna dan nilai kehidupan, tetapi hanya untuk memburu gelar-gelar kesarjanaan. Negeri kita adalah negeri ‘gila gelar’. Di saat seperti inilah, kita berharap ada pemuda-pemuda yang mau terbesit hatinya untuk menangani kiris budaya baca ini. Pertanyaannya: adakah pemuda-pemuda seperti itu? Bagaimanakah strategi-strategi taktis menangani rendahnya budaya baca di negeri kita?
***
Saya berasal dari sebuah negeri yang resminya sudah bebas buta huruf, namun yang dipastikan masyarakatnya sebagian besar belum membaca secara benar—yakni membaca untuk memberi makna dan meningkatkan nilai kehidupannya. Negara kami adalah masyarakat yang membaca hanya untuk mencari alamat, membaca untuk harga-harga, membaca untuk melihat lowongan pekerjaan, membaca untuk menengok hasil pertandingan sepak bola, membaca karena ingin tahu berapa persen discount obral di pusat perbelanjaan, dan akhirnya membaca subtitle opera sabun di televisi untuk mendapatkan sekadar hiburan.
Cuplikan pidato Seno Gumira Ajidarma dalam penerimaan South East Asia (SEA) Write Award 1997 di atas sekilas menggambarkan kegelisahan yang luar biasa: betapa fenomena keilmuan masyarakat Indonesia tidak didasari pada gairah untuk membaca dengan benar. Ya! Suatu bangsa yang berpopulasi lebih dari 200 juta jiwa ini pada umumnya membaca hanya untuk mengisi waktu (to fill time), bukan membaca untuk menghabiskan waktu (to kill time).
Ironis memang. Karena di tengah maraknya propaganda terbitnya fajar baru kebebasan berekspresi yang diusung oleh Orde Reformasi setelah sekian lama berjuang melawan otoritas Orde Baru, bangsa ini masih belum bisa keluar dari kemelut 'lingkaran setan' dalam menangani rendahnya minat baca buku masyarakatnya. Bahkan, sekadar untuk meminimalisir angka buta huruf saja, Indonesia masih tersendat-sendat dan selalu menemui jalan buntu.
Dalam masalah tingkat sadar baca, masyarakat negeri ini juga belum menunjukkan kabar yang menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa keterampilan dan minat baca pelajar tingkat dasar di Indonesia paling terbelakang di antara negara-negara Asia yang lain. Menurut laporan tersebut, Hongkong menempati posisi teratas dengan persentase angka minat baca 75,5 persen, di bawahnya ditempati Singapura dengan angka 74,0 persen, kemudian Thailand dengan angka 65,1 persen, lalu di belakangnya ada Filipina dengan angka 52,6 persen, dan yang paling buntut adalah Indonesia dengan angka hanya 51,7 persen. Tidak berlebihan jika Muhammad al-Fayyadl, kritikus muda sastra, sampai mengatakan bahwa bangsa ini masih terjangkit suatu penyakit yang cukup kronis. Ia menyebutnya sebagai ”malnutrisi buku!” Tidak hanya itu, daya beli masyarakat yang rendah, guru dan tenaga pengajar yang 'malas' membaca, penyaluran buku yang tidak merata, pengelola perpustakaan yang tak ramah baca, kurangnya motivasi orang tua pada anak, hingga animo miring soal pecinta buku yang sering dijuluki 'kutu' buku justru semakin menghambat tumbuhnya budaya baca di negeri ini.
Apalagi, dalam dekade sepuluh tahun terakhir, media televisi mengisi hampir 50 persen dari waktu senggang malam hari masyarakat Indonesia yang berpendidikan sekolah menengah. Sampai-sampai M. Mustafa, editor freelance untuk penerbit Serambi Jakarta dan editor buku non-fiksi pada penerbit Bentang Yogyakarta, menyebut masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bergerak cepat; dari suatu keadaan pre-literer ke dalam keadaan pra-literer; dari suatu lingkungan masyarakat yang tak pernah membaca ke dalam suatu lingkungan yang tak hendak membaca. Padahal, menurut Sadli, "buku adalah yang paling insightful dan kaya. Media TV dan radio bisa memberi kilasan-kilasan pendek (short insight) yang cuma bisa memperkaya wacana, cukup untuk updating...."
Lalu, masihkah ada alasan untuk tidak mencintai buku?
***
Ada kejahatan yang lebih buruk dari membakar buku, salah satunya adalah tidak membaca buku. (Joseph Alexandrovitch Brodsky, 1940-1996)
Pengetahuan sebagian besar tidaklah didapatkan dari bangku sekolah, melainkan melalui buku. (Ajip Rosidi)
Sekolah tanpa perpustakaan bagiku bukan sekolah. Pelajar tanpa buku bagiku bukan pelajar. (Minda Perangin-Angin)
Konon, seseorang bisa terjangkit suatu penyakit disebabkan oleh buku. Penyakit tersebut adalah biblioholisme, suatu penyakit yang membuat penderitanya selalu berhasrat untuk membeli, membaca, menyimpan, dan mengagumi buku.
Ada dua jenis penyakit biblioholisme ini, yaitu bibliomania (gila buku) dan bibliofil (cinta buku). Sebenarnya kedua penyakit ini mempunyai persamaan dalam menganggap buku sebagai sesuatu yang berharga, hanya saja jika bibliomania membeli buku sekadar untuk menumpuknya, sedangkan bibliofil berharap dapat menguras isi dan kebijakan dari buku-buku tersebut. Tentunya, kuantitas buku lebih banyak dimiliki oleh bibliomania ketimbang bibliofil, yang membedakan keduanya hanya sebatas motivasi.
Boulard, ahli hukum asal Prancis yang hidup pada abad ke-18, adalah salah seorang tokoh yang terjanggit penyakit bibliomania. Boulard begitu bernafsu memiliki buku, hingga rumahnya tak cukup menampung buku-bukunya—sampai-sampai ia harus membeli enam rumah lagi. Orang yang hendak bertamu ke rumahnya harus ekstra hati-hati kalau tidak mau tertimbun longsoran buku. Hingga akhir hidupnya, Boulard memiliki 600 ribu - 800 ribu jilid buku. Problem kegilaan Boulard: ia tak membaca buku yang ia beli.
Sedangkan bibliofil lebih waras dan bijak: banyak membeli dan banyak membaca. Richard Heber asal Inggris dan hidup pada abad ke-19 adalah contohnya. Sama dengan Boulard, koleksinya yang berjumlah 200 ribu – 300 ribu buku memaksa ia memiliki delapan rumah: dua di London dan enam lainnya tersebar di Inggris dan Eropa. Beda dengan Boulard, Heber selalu membaca bahkan sampai akhir hayatnya.
Dari kedua penyakit ini, tentunya kita mengharapkan sebuah bangsa yang warganya ‘mengidap penyakit’ bibliofil; sebuah komunitas yang bernafsu memiliki segudang buku dan benar-benar memanfaatkannya dengan benar untuk kehidupan masa depan, dan demi keberlangsungan peradaban; suatu bangsa yang nantinya mampu melahirkan intelektual-intelektual ternama dengan sejagat pengetahuan dan wawasan yang dimiliki; sebuah bangsa yang sangat menghargai buku sebagai pedoman hidup (way of life), bahkan menjadikannya sebagai kekayaan negara yang para warganya memilki hak untuk menikmati, mengapresiasi, dan membacanya.
Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa bibliofil adalah perpustakaan. Dengan segala keterbatasan daya beli masyarakat, perpustakaan tentunya merupakan harapan ‘emas’ bangsa yang perlu diberdayakan demi terwujudnya bangsa bibliofil ini. Hadirnya perpustakaan di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat mendongkrak minat dan gairah membaca mereka dalam membaca buku.
Kita layak meniru keberhasilan India dan Amerika dalam pengembangan negara melalui perpustakaan. Di India, ada Jawahral Nehru yang membentuk semacam perpustakaan megah National Book Trust dan Sahitya Academy. Berkat keberhasilannya memberantas buta huruf melalui program yang dirancang oleh perpustakaan tersebut, pada tahun 1999 negara yang pendapatan per capitanya tidak berbeda terlalu jauh dengan Indonesia ini memperoleh penghargaan dari UNESCO berupa UNESCO's Noma Literacy Prize. Di Amerika, ada Thomas Jefferson, penulis The Declaration of Independence AS yang terkenal dengan kata-katanya "I can't live without books!", berhasil mendirikan The Library of Congress yang menjadikan Amerika waktu itu merdeka dan menjadi negara maju saat ini.
Kini saatnya kita mewujudkan perpustakaan yang benar-benar menjalankan tanggung jawab demi terciptanya masyarakat baca dan masyarakat pecinta buku. Beberapa strategi taktis yang penulis dapat tawarkan untuk pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan ke depan antara lain:
Pertama, ketersediaan bahan pustaka yang sesuai bagi para pembaca. Secara praksis, menurut Taufiq Ismail, pengembangan budaya baca (siswa) harus dimulai dari cerita anak-anak (SD), dilanjutkan dengan pengenalan kepada karya-karya sastra (SMP), kemudian ke buku-buku lain seperti biografi, agama, sejarah, dan sebagainya (SMA).
Kedua, penjaga yang ramah dan murah senyum. Agaknya, perpustakaan-perpustakaan masa kini perlu meniru strategi perpustakaan Ignatius di Yogyakarta. Walaupun arealnya tak seberapa luas, suasana yang sejuk serta pelayanan yang ramah dan simpatik menjadikan taman baca yang dikelola kaum Nashrani ini mampu memikat banyak orang dari berbagai agama untuk bertandang dan menjadi anggota tetap di sana. Perpustakaan harus mampu menjadi sentrum pembelajaran (learning center) yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu (kuriositas) para pembaca hingga tak mudah mencapai titik jenuh.
Ketiga, waktu yang panjang untuk para pembaca. Penulis pernah membayangkan bagaimana jadinya perpustakaan buka sampai larut malam, tentunya kita dapat membaca, menulis, dan bermeditasi dalam samudera pengetahuan dengan tenang tanpa diburu waktu. Memperpanjang jam buka perpustakaan juga dimaksudkan agar intelegensi kita dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Suatu riset menyebutkan bahwa tingkat kesuksesan, intelegensi, dan kemampuan seseorang dinilai dari seberapa besar waktu yang digunakan untuk membaca.
Keempat, pembentukan klub baca. Di Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep, Madura, misalnya, ada Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) yang terlibat aktif dalam sosialisasi komik GEBORA kepada anak-anak. Salah satu aplikasi program ini adalah membentuk klub baca siswa untuk mendiskusikan komik tersebut dalam satu minggu untuk satu kali pertemuan. Hasilnya, para siswa yang kebanyakan masih duduk di bangku SLTP ini begitu aktif mengikuti diskusi tersebut dan terus menggali ilmu pengetahuan melalui membaca buku pengayaan lain.
Kelima, revolusi paradigmatik. Penjaga perpustakaan harus mampu mempersepsikan membaca sebagai suatu yang familiar kepada masyarakat. Proses ini mungkin tepat jiika dikorelasikan dengan gagasan Hernowo tentang 'buku sebagai sepotong pizza'. Tentunya, mereka harus menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat membaca buku dan fungsinya untuk masa depan mereka.
Ketujuh, pemberdayaan perpustakaan secara edukatif, seperti intensifikasi libraryschool dan silent reading program yang pernah dilaksanakan oleh Nanyang Primary School, Singapura. Sekolah ini meluangkan waktu dari pukul 07.00 sampai 07.30 kepada siswa untuk membaca buku dalam kelas.
Akhirnya, upaya-upaya di atas diharapkan mampu membangun bangsa bibliofil; bangsa yang mempunyai warga pecinta buku dan menjadikan buku sebagai kekayaan dan aset terbesarnya. Komunitas pecinta buku (bibliofil) adalah mereka yang benar-benar memanfaatkan buku dan mengambil kebijakan dari buku yang dibacanya. Mungkin, jika boleh berandai, penulis ingin mendengar lagi sosok manusia seperti Jorge Luis Borges, seorang multitalenta yang gila buku dan pengidap penyakit bibliofil akut dengan kebiasaannya yang begitu absurd, seorang legendaris penjaga perpustakaan Argentina yang matanya nyaris buta. Kata-katanya yang melenakan itu: "I have imagined that paradise will be a kind of library!" (Saya telah membayangkan bahwa surga menjadi bagian dari perpustakaan!). []
*) Achmad Fawaid
Bukan Pembaca Buku Serius, Mahasiswa Doktoral FIB UGM Yogyakarta
Esai ini memperoleh penghargaan Esai Terbaik ke-2 dalam Kompetisi Esai Menjadi Indonesia yang diselenggarakan oleh Tempo Institute pada tahun 2014. Dapat diakses pula di https://indonesiana.tempo.co/read/9132/2014/02/12/faaid_achmed/perpustakaan-budaya-baca-dan-bangsa-bibliofil. Dimuat kembali untuk edukasi.