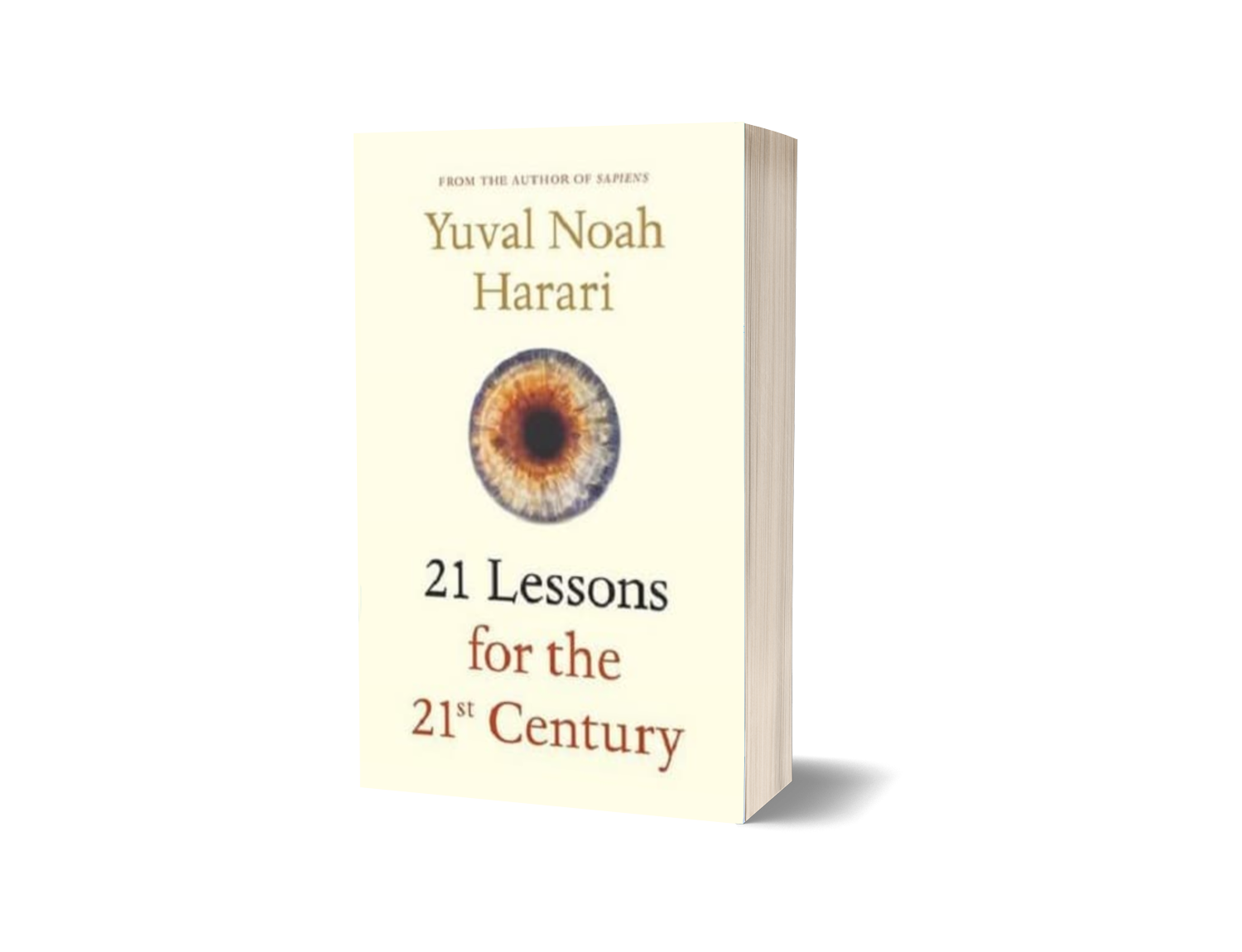Setelah dua buku sebelumnya, Homo Sapiens dan Homo Deus mengguncang jagad literasi, Yuval Noal Harari menyodorkan karya ketiga, yang menggagas 21 pelajaran di abad ke-21. Dari kalimat pertama, kita bisa membayangkan kepiawaian dosen Universitas Hebrew tersebut dalam menganggit gagasan. Di dalam sebuah dunia yang dibanjiri oleh informasi yang tidak relevan, kejelasan adalah kekuatan. Dalam dunia serba internet, setiap pengguna sejatinya bisa mengakses data, tetapi pada masa yang sama mereka dihadapkan dengan keberlimpahan maklumat dan tanpa disadari memasuki labirin.
Sesudah mengurai sejarah masa lalu manusia pada karya pertama dan perkembangan evolusioner yang menyebabkan individu bisa menyerupai Tuhan pada buah pikiran yang kedua, lalu apa yang terjadi pada masa kini, tantangan dan pilihan yang tersedia? Apa yang mesti kita beri perhatian? Dan apa yang seharusnya kita ajar pada anak-anak? Pertanyaan ini tampak mudah, namun hakikatnya mengandaikan pelbagai pendekatan dan pandangan. Buku ini menyodorkan kekayaan perspektif yang memantik perenungan.
Mengingat begitu luas isu kemanusiaan, penulis hendak menghadirkan perspektif global terhadap kekuatan utama yang membentuk masyarakat seluruh dunia. Dengan memahami apa yang mungkin terjadi pada masa depan, maka dua puluh satu isu yang dibahas dengan cemerlang akan menuntut banyak orang untuk memikirkan kembali apa yang diyakini hari ini sebagai jalan yang harus ditempuh atau perlu ditinjau ulang karena orang ramai melakukan hal serupa untuk hasil yang berbeda. Ada dua istilah kunci yang akan mengubah corak kehidupan pada masa yang akan datang, teknologi informasi dan teknologi biologi.
Sebagai pemikiran spekulatif, Yuval bermain dengan angka. Dengan menjadikan abad ke-21 sebagai era yang perlu diungkap, filsuf ini menawarkan 21 isu utama yang mesti diselesaikan, yang dibagi ke dalam empat bagian besar, yaitu tantangan teknologi, politik, harapan dan keputusasaan, kebenaran serta daya tahan. Dengan demikian, pembaca diajak untuk melihat gambar hidup lebih besar, bukan sekadar pertentangan orientasi politik, kubu paham ideologis, dan pertentangan kelas, apalagi terseret pada dunia baru yang hendak dibangun oleh Amerika Serikat.
Di tengah gejolak politik tanpa henti, manusia menghadapi ancaman lain yang tak kalah beratnya, peluang pekerjaan. Dua tipe kemampuan manusia, yang bersifat fisik dan kognitif, akan digantikan oleh mesin. Pekerjaan kasar dalam bidang pertanian dan industri bertukar automasi, sementara keterampilan akal budi, seperti pembelajaran, penganalisisan, komunikasi, telah dibayangi oleh kedigdayaan kecerdasan buatan (Artificial intelligence), bahkan yang terakhir sekarang mulai melebihi kemahiran manusia, termasuk memahami emosi seseorang. Tak pelak, pekerjaan pengacara mungkin akan digantikan dengan mesin konsultasi yang didukung oleh algoritma. Lebih jauh, dengan komputasi algoritma, sebuah mesin komputer akan mampu memahami hasrat manusia, termasuk orientasi seksualnya. Tidak hanya itu, jenis pekerjaan dan jurusan studi bisa dibantu dipecahkan.
Dengan kemajuan teknologi ini, adakah daya pikir warga itu terkerek? Lagi-lagi, pilihan politik atau referendum itu didasarkan pada perasaan, bukan rasionalitas. Orang sekelas Richard Dawkins, ahli biologi ternama, memprotes bahwa mayoritas warga Inggris, termasuk dirinya, tidak mempunyai pengetahuan yang diperlukan dalam bidang ekonomi dan sains politik. Buruk atau baik, pemilihan umum itu tak terkait dengan apa yang kita pikir. Tidak ada bedanya antara Albert Einstein dan Ahmad yang bekerja sebagai pemulung dalam menentukan dukungan politik. Sementara, penguasa data besar (big data) bisa bekerja untuk pemerintah atau perusahaan untuk menjual kecenderungan pilihan warga terhadap politik atau barang.
Sejatinya, dengan bantuan teknologi, manusia bisa melakukan banyak pekerjaan lebih mudah dan mendapatkan hasil lebih banyak. Kenyataannya, jam kerja mereka tak berkurang, dan pendapatan tak naik secara signifikan. Malangnya, abad ke-21 adalah kurun kesenjangan yang paling besar dalam sejarah manusia. Jurang pemisah ini tidak lagi diukur dari penguasaan tanah, seperti pada zaman revolusi pertanian, tetapi penguasaan data. Untuk itu, agar kita bisa melindungi pemusatan semua kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir elit, kuncinya adalah mengatur kepemilikan data, yang dikangkangi oleh Google, Facebook, Baidu, dan Tencent. Apa lacur, pengguna telah terperangkap dengan janji kaum libertarian bahwa kebebasan akan melempangkan jalan pada kemajuan bersama.
Dalam keadaan individu makin mudah mengakses temuan baru, adakah agama akan mengalami kemunduran? Tidak. Tetapi, Yuval menyuguhkan ulasan menarik. Mungkin di abad tengah, kitab suci bisa menjadi pedoman, tetapi adalah ia masih relevan pada era kecerdasan buatan, rekayasa biologi, pemanasan global dan perang cyber? Kenyataanya, jutaan manusia masih percaya pada Alqur’an dan Injil berbanding pada teori evolusi manusia. Untuk itu, Yuval mengajukan pertanyaan, adakah kaum agamawan bisa menyelesaikan tantangan baru, seperti pemanasan global? Ulama Iran akan mendorong warga untuk melihat isu ini dari perspektif Syi’ah, rabi Yahudi mengusulkan apa yang terbaik bagi orang Israel, demikian pula pendeta ortodoks Rusia mengutamakan kepentingan negeri Beruang Merah. Mengingat isu ini bersifat global, agama jelas tidak relevan untuk menjawab, apalagi mengatasi persoalan.
Selanjutnya, sejarawan Israel tersebut mendorong manusia untuk berbicara tentang kebenaran, keadilan, pasca kebenaran dan sains fiksi, yang membongkar banyak mitos atas nama pandangan dunia tertentu. Dengan pelbagai sumber kritis dan kepercayaan yang rasional, bagaimana kita bisa menghadapi keadaan kaotik ini? Jawaban Yuval tampak klise, pendidikan. Di sini, pelajar harus belajar bagaimana menjaga kestabilan dan keseimbangan mental serta menemukan diri sendiri. Dengan mengakhiri bagian akhir berupa meditasi, buku ini sesungguhnya belum melahirkan gagasan baru tentang makna menjadi manusia. Ide filsafat dan agama sejak awal menempatkan pengenalan diri sebagai jalan menuju kebenaran dan Tuhan. Dengan melatih napas berjalan teratur dalam praktik Vipassana, yang berarti instropeksi, pembaca bisa menangguk pelajaran bahwa selagi diri sendiri cukup untuk mengada di dunia, maka benda baru yang dihasilkan adalah objek tafsir yang tidak secanggih struktur kesadaran manusia.
Ahmad Sahidah*
*Dosen Filsafat Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Nurul Jadid